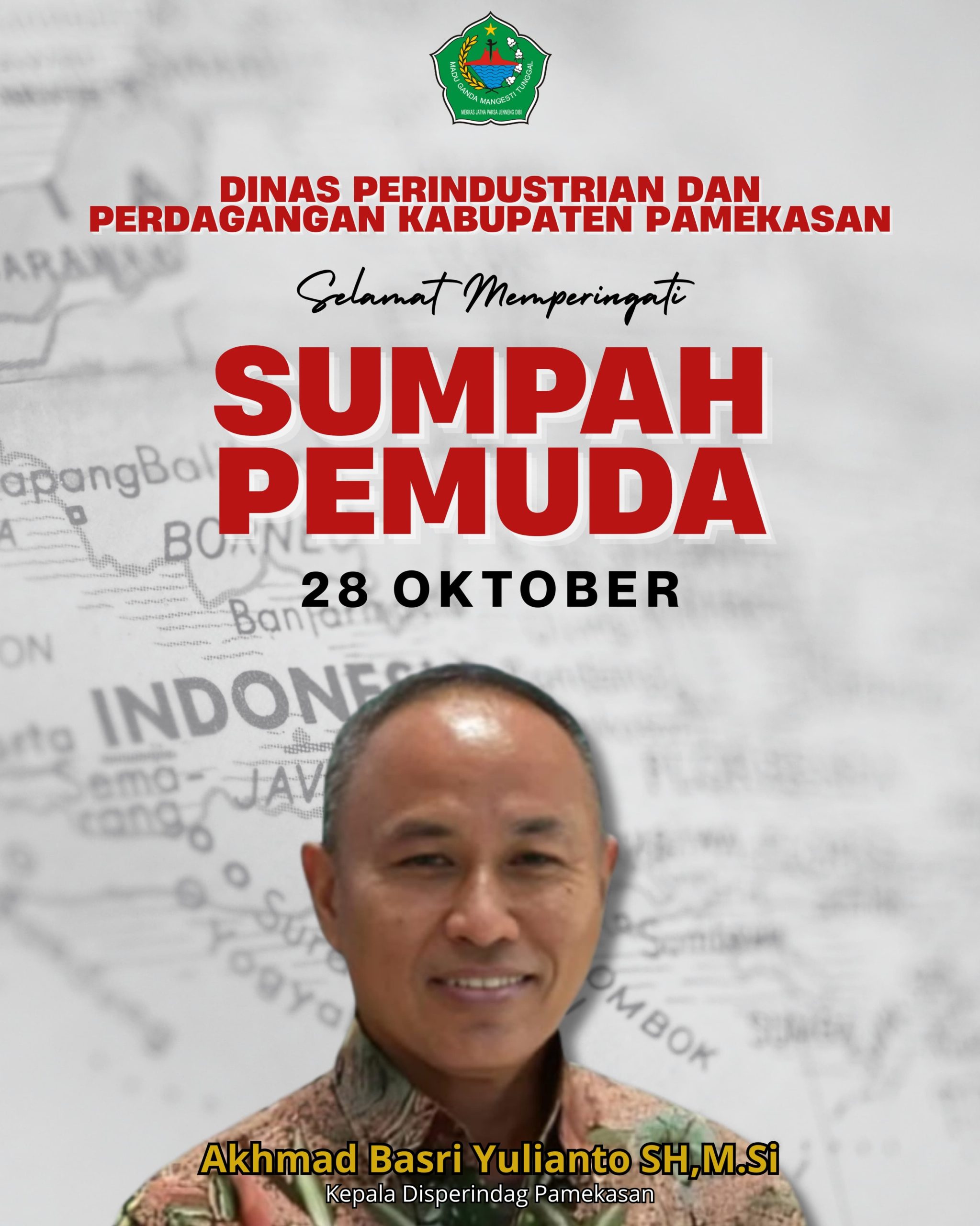Oleh: Yuski Al Faruq (PK PMII STKIP PGRI Situbondo)
ISSUE, Essai. Beberapa waktu terakhir, publik dikejutkan oleh tayangan di salah satu stasiun televisi nasional, Trans7, yang dinilai menyinggung kehormatan seorang kiai sepuh dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Tayangan tersebut memicu gelombang protes dari kalangan pesantren, santri, hingga organisasi keagamaan. Mereka menilai ada narasi dalam tayangan itu yang tidak patut disampaikan kepada publik karena berpotensi merendahkan marwah ulama yang selama ini dihormati umat.
Sebagian orang mungkin menganggap kasus ini hanya kesalahpahaman atau bentuk kebebasan berekspresi. Namun jika ditelaah lebih dalam, persoalan ini menyentuh hal yang jauh lebih mendasar: tentang adab terhadap ulama, etika komunikasi di ruang publik, serta batas kebebasan media dalam masyarakat yang beragama.
Dalam pandangan Islam, ulama bukan sekadar tokoh masyarakat. Mereka adalah penjaga moral dan pewaris pengetahuan para nabi. Rasulullah ﷺ bersabda, “Ulama adalah pewaris para nabi.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Karena itu, kehormatan ulama bukan hanya milik pribadi, melainkan bagian dari kehormatan umat dan agama itu sendiri. Menyebut atau menggambarkan seorang ulama dengan cara yang tidak sopan berarti mencederai nilai keagamaan yang mereka wakili.
Al-Qur’an menegaskan pentingnya adab terhadap tokoh mulia dalam surah Al-Hujurat ayat 2:
“Janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, agar tidak gugur amalmu tanpa kamu sadari.”
Ayat ini mengandung pesan universal tentang adab terhadap pewaris ilmu kenabian. Dalam tradisi pesantren, adab kepada kiai bahkan dianggap lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Maka, ketika media menayangkan narasi yang menyinggung kehormatan ulama, itu bukan sekadar kesalahan jurnalistik, tetapi juga pelanggaran nilai spiritual.
Dari sisi hukum, pijakannya pun jelas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran melarang isi siaran yang menghina atau menistakan nilai agama. Demikian pula Pedoman Perilaku Penyiaran KPI mewajibkan lembaga penyiaran menghormati norma agama dan tokoh keagamaan. Dengan demikian, tayangan yang memuat unsur pelecehan terhadap ulama dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika penyiaran.
Sebagian berpendapat tidak ada niat buruk dalam tayangan tersebut. Namun dalam etika komunikasi publik, dampak jauh lebih penting daripada niat. Ketika sebuah tayangan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap media, tanggung jawab moral tetap berada di pundak penyiar. Kebebasan pers memang dijamin konstitusi, tetapi kebebasan itu harus dijalankan dalam koridor tanggung jawab sosial dan penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan bangsa.
Dalam khazanah Islam, dikenal prinsip sadd adz-dzari‘ah, yakni menutup jalan menuju kerusakan. Setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan fitnah atau keresahan sosial harus dihindari. Tayangan yang menyinggung ulama jelas memiliki potensi destruktif, baik moral maupun sosial. Karena itu, langkah tabayun dan permintaan maaf terbuka dari pihak media merupakan keharusan untuk memulihkan kepercayaan publik.
Ulama sepuh seperti yang ada di Lirboyo bukan sekadar figur karismatik bagi santrinya, melainkan simbol kebijaksanaan dan penjaga warisan ilmu Islam yang menuntun arah moral bangsa selama berabad-abad. Ketika kehormatan seorang ulama direndahkan di ruang publik, dampaknya tak berhenti di satu pesantren saja. Ia menjalar ke seluruh jaringan pesantren dan umat Islam yang menaruh hormat kepada para guru agama.
Tayangan yang menyinggung ulama dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keulamaan dan pendidikan Islam tradisional. Dalam masyarakat yang kian skeptis terhadap otoritas moral, peristiwa semacam ini bisa menumbuhkan keraguan terhadap ketulusan ulama membimbing umat. Padahal pesantren dan para kiai telah lama menjadi benteng akhlak, kesantunan, dan spiritualitas bangsa. Hilangnya rasa percaya terhadap mereka sama saja dengan hilangnya pedoman moral yang menuntun peradaban.
Penting pula diluruskan pandangan keliru bahwa menghormati atau bertakdim kepada guru dan ulama adalah tradisi feodal. Dalam tradisi pesantren, takdim bukanlah penghambaan kepada manusia, melainkan penghormatan terhadap ilmu dan akhlak yang Allah titipkan melalui para guru. Seorang santri mencium tangan kiainya bukan karena tunduk pada kekuasaan, melainkan karena sadar bahwa ilmu tidak akan berbuah tanpa adab. Sikap takdim ini merupakan ekspresi spiritual seorang pencari ilmu yang menyadari bahwa pengetahuan sejati lahir dari kerendahan hati.
Maka, ketika ruang publik memperlakukan ulama dengan nada yang menyinggung, yang dirusak bukan hanya nama seorang kiai, tetapi juga jaringan nilai-nilai luhur yang selama ini menjaga harmoni sosial umat. Kehilangan rasa hormat terhadap ulama berarti kehilangan arah dalam menghargai sumber kebijaksanaan. Sebab di tangan para ulama, ilmu bukan hanya teori, melainkan cahaya yang menerangi kehidupan bersama.
Rasulullah ﷺ bersabda, “Barang siapa tidak menghormati orang tua kami, tidak menyayangi yang muda, dan tidak memuliakan ulama, maka ia bukan termasuk golongan kami.” (HR. Ahmad). Hadis ini menegaskan bahwa menghormati ulama bukan sekadar sopan santun, tetapi bagian dari identitas keislaman. Karena itu, reaksi keras kalangan pesantren bukanlah fanatisme berlebihan, melainkan ekspresi cinta dan pembelaan terhadap marwah agama.
Akhirnya, peristiwa ini semestinya menjadi pelajaran bagi seluruh media. Kebebasan berekspresi bukan alasan untuk mengabaikan etika dan nilai-nilai spiritual bangsa. Dalam masyarakat religius seperti Indonesia, media yang beradab bukanlah yang berbicara paling keras, melainkan yang tahu kapan harus berhenti agar tidak melukai hati umat.